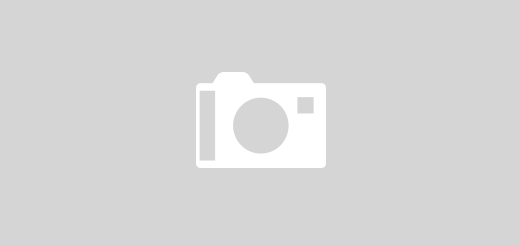Desa Waerebo

Waerebo merupakan sebuah kampung adat di daerah Manggarai, Flores, yang masih dihuni hingga saat ini dan warganya meyakini bahwa para leluhur mereka masih tinggal bersama. Mereka masih taat menjalankan adat istiadat, menghormati para leluhur serta hidup harmonis dengan hutan dan ekosistemnya.
1 Juni 2015 lalu, gue berkesempatan untuk mengunjungi Desa tersebut bareng teman-teman Komodo trip. Gue tiba di Waerebo Lodge – sebuah penginapan di tepi sawah – jam 11 siang. Gue tidak menginap disana tapi hanya untuk sekedar istirahat setelah 8 jam perjalanan darat dari Bajo dan makan siang sebelum memulai trekking. Dari sana, gue menuju ke titik start trekking dengan menggunakan mobil selama 30 menit. Gue baru mulai trekking jam 13.15. Jalur trekking yang harus gue lewati berupa jalan yang sudah tersusun rapih dengan bebatuan kali sepanjang 3,8 km yang dilanjutkan dengan masuk ke dalam hutan dengan total jarak trekking keseluruhan adalah 9 km.
Saat memulai trekking gue berjalan paling belakang ditemani pak Eman, guide kami. Kondisi gue saat itu sedang flu, jadi gue memilih untuk trekking santai. Pak Eman sempat mengambilkan sebuah tanaman sampai ke akarnya dan dia meminta gue untuk mencium akar tanaman tersebut. Setelah gue mencium, wanginya berasa kaya balsem. Dan benar saja, tanaman itu memang salah satu bahan pembuat tiger balm. Karena hidung yang agak mampet, akhirnya gue nyiumin akar tanaman itu terus sampe berasa lega.
Pak Eman juga bercerita bahwa medan trekking bebatuan akan di aspal supaya mobil bisa lewat dan memperpendek jalur trekking. Di satu sisi gue seneng dengan harapan semakin banyak orang yang bisa dengan lebih mudah mengunjungi desa Wae Rebo, tapi di sisi lain gue berasa lebih asik kalo kita sembari trekking. Lebih bisa menikmati alam sekitar yang penuh dedaunan hijau, udara yang segar dan gemercik air di beberapa bagian jalan. Tapi, yasudahlah.
Gue terus berjalan hingga akhirnya menemui sebuah sumber air. Dan ternyata itu sebagai tanda bahwa gue sudah mendekati pos 1.
Di pos 1, gue beristirahat sejenak bareng dengan Rena, Hans, Esther, Harun dan Aank. Disana gue membaca 7 pesan masyarakat yang beberapa diantaranya adalah :
– Hormatilah alam sekitar dengan membiarkan alam apa adanya
– Ciptakan suasana nyaman dengan membawa kembali sampah anorganik
– Jaga keselamatan dengan mentaati rambu jalan
– Hormati otoritas lokal
Satu hal yang pasti, 7 pesan masyarakat Wae Rebo harus dilaksanakan demi kesalamatan kita selama berkunjung disana. Dari pos 1, kami mulai memasuki kawasan hutan dengan dengan medan trekking berupa tanah seperti gambar dibawah ini
Medan pendakian berupa tanjakan namun tidak terlalu curam sehingga tidak begitu sulit untuk dilewati. Saat melewati hutan kita bisa lihat berbagai macam tumbuhan hijau serta bisa mendengarkan suara satwa yang ada di dalamnya. Kondisi saat kami trekking mulai berkabut yang membuat pandangan mata menjadi tidak begitu jauh, namun tetap berhasil untuk memanjakan mata serta menyegarkan pernapasan.
Uniknya disini setelah kita trekking sejauh 4,55 km kita akan menjumpai plang yang menunjukan sisa jarak yang harus kita tempuh. Di satu sisi plang tersebut bikin kita semangat terus melaju karena bisa mengukur jarak yang sudah kita tempuh tapi di sisi lain bikin kita frustasi karena merasa nggak nyampe-nyampe. HAHAHA. Tapi itu semua tergantung kita memandang dari sudut yang mana sih :p
Pos 2 trekking berada di sisa pendakian 2,7 km. Bentuk pos trekking disana bukanlah berupa dataran kosong luas namun sekedar jalur biasa dimana ada banyak bebatuan besar yang sekiranya bisa kita gunakan untuk beristirahat sejenak 🙂
Lanjut trekking menanjak kembali hingga tersisa 2,4 km. Disanalah kami menjumpai medan trekking yang cukup datar sampai jalur tersisa 1,7 km. Disanalah kami bisa tersenyum lebar sambil berjalan. Psstt..kalo sebelumnya kan harus atur nafas dan langkah kaki yah biar nggak cepet capek :p
Plang penanda sisa jalur trekking pun terus kami jumpai sampai akhir jalur trekking.
Sebelum tiba di Desa Wae Rebonya, kami beristirahat di Rumah Kasih Ibu yang berjarak 500m dari desa. Disana kami menunggu rombongan lain yang belum sampai, supaya nantinya kami dapat melakukan upacara adat bersama-sama. Rumah Kasih Ibu sendiri lebih menyerupai pendopo yang berbentuk panggung terbuat dari kayu dengan anyaman bambu di bagian sampingnya.
Setelah semua rombongan tiba, kami bersiap untuk masuk ke dalam Desa Wae Rebo. Pak Martin, guide lokal yang merupakan warga Wae Rebo itu sendiri mengingatkan kami untuk tidak mengambil foto terlebih dahulu pada saat memasukinya. Kami harus melaksanakan upacara adat dahulu yang bertujuan untuk memohon ijin kepada leluhur bahwa ada tamu yang berkunjung supaya nantinya tamunya tidak diganggu dan dapat bermalam dengan tentram, aman, damai dan sentosa.
Pak Martin memimpin rombongan memasuki desa Wae Rebo dengan menggunakan sarung dan ikat kepala diatasnya. Kami memasuki rumah kepala adat, Pak Alex, untuk memulai upacara adat. Kami duduk di sekeliling rumah setengah lingkaran dan pak Alex berada di tengah depan kami. Intinya, Pak Martin menyampaikan bahwa ada tamu kepada Pak Alex sembari memohon izin agar tamu yang datang bisa menjadi bagian dari warga Wae Rebo sekaligus memohon ijin kepada para leluhur. Kemudian Pak Martin memberikan sedikit uang kepada pak Alex lalu pak Alex berbicara kepada leluhur. Acaranya cukup sederhana namun wajib dilakukan. Pak Alex dan Pak Martin menggunakan bahasa setempat yang kemudian di alih bahasakan supaya kami mengerti. Ya, intinya seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Mereka sangat bangga loh kedatangan tamu dari Jakarta, yang menurut mereka tamu dari Ibu Kota negara Republik Indonesia 🙂
Selesai upacara adat, kami pindah ke rumah Mbaru Niang (sebutan rumah adat sana) khusus tamu untuk bermalam disana. Bedanya dengan rumah lain adalah posisi dapur, toilet serta kamar mandi berada di luar. Sedangkan rumah asli Mbaru Niang yang ditempati warga Wae Rebo semua fasilitasnya ada di dalam. Semua di desain seperti itu karena ada tamu yang tidak kuat dengan asap saat masak dan tidak terbiasa dengan kondisi toilet yang digabung dengan tempat tidur.
Kami masuk ke dalam rumah kemudian mencari posisi masing-masing untuk memilih tempat tidur di sekeliling rumah dan juga berfoto bersama sebagai bukti otentik bahwa kami pernah bermalam disana 😀
Dari sana, Pak Martin menjelaskan juga bahwa warga menjual berbagai hasil karya tangan seperti kain tenun dengan harga 500 ribu, kopi dengan rentang harga 50 – 200rb dan gelang seharga 25ribu.
Setelah itu, gue langsung memilih untuk tidur setelah meminum obat flu yang bikin ngantuk lalu dibangunkan pukul 9 malam untuk makan. Selesai makan pun, gue langsung tidur lagi hingga pagi dan gue terbangun pukul 5 pagi.
Gue langsung bergegas untuk mandi dengan dinginnya air yang bikin gemeteran. Udara disana juga cukup dingin yang mengharuskan gue buat pake pakaian rangkap 2. Selesai mandi, gue keluar dari rumah dan mendapati kabut pagi yang cukup tebal. Di luar gue menikmati udara sembari menunggu cerahnya langit. Sekitar jam 6, Pak Martin mengajak beberapa dari kami menuju rumah baca dengan berjalan sekitar 500 meter ke atas. Bukan ke arah Rumah Kasih Ibu yah, tapi ke sisi satunya lagi. Dari rumah baca-lah, kita bisa mendapati gambar desa Wae Rebo secara keseluruhan.
Selesai dari sana, gue dan Esther bermain ke rumah warga. Pagi hari, ibu-ibu di dalam rumah sedang sibuk masak untuk sarapan. Anak-anak bermain di dalam rumah dan para Bapak ada yang berkebun, membuat keranjang dan lain sebagainya.
Perlu diketahui untuk Mbaru Niang yang paling besar merupakan tempat tinggal kepala adat, di dalamnya ada 8 keluarga yang tinggal. Sedangkan untuk Mbaru Niang lainnya ditempati oleh 6 keluarga. Total jumlah KK (Kartu Keluarga) yang tercatat saat gue kesana dalah 117 KK, sisanya tinggal di daerah sekitar dengan rumah panggung biasa. Karena biaya untuk pembangunan Mbaru Niang cukup mahal 🙂
Setelah mengunjungi rumah warga, gue mengajak anak mereka bermain ke luar. Ada Nafia, Avel, Tris, berto, Tori, Beti dan yang lainnya. Bermain ular naga panjang, domikado dan sesekali menggendong Nafia yang masih berusia 8 bulan membuat pagi gue terasa lebih bermakna. Inilah mereka teman main gue pas disana 🙂
Banyak hal yang bikin gue kagum sama anak-anak disana, semuanya ramah. Kalao ketemu orang baru mereka akan menyapa dengan “halo” atau “selamat pagi” sambil tersenyum. Dan berasa banget mereka melakukannya dengan tulus. Jadi buat kita yang disapa juga rasanya adeeemmm.
Nggak cuma anak-anaknya, dari bapak-bapak, ibu-ibu samapai kakek nenek semuanya ramah. Langka banget bisa nemuin hal seperti itu di Jakarta, khususnya. Ditambah lagi alam disana yang luar biasa cantiknya membuat pengalaman gue menjadi lebih sempurna.
Semua warga disana beragama Katolik dan setiap Minggunya untuk mereka bisa beribadah berarti mereka harus berjalan 18 km bolak balik. Salut! Ah ya, pas di dalam perjalanan trekking menuju desa Wae Rebo, ada seorang kakek tua yang trekking turun ke bawah hanya untuk suntik karena sedang sakit kemudian kembali trekking lagi menuju rumahnya. LUAR BIASA! Semacam refleksi diri buat kita yang masih muda tapi suka malas-malasan 🙂
Setelah bermain bersama warga disana, kami segera packing sarapan dan turun kebawah. Buat trekking ke bawah memakan waktu sekitar 3 jam. Secara waktu tempuh lebih cepat tapi untuk medannya tidak lebih mudah dari yang gue bayangkan 🙂 Kembali ke Wae Rebo Lodge kami disuguhkan makan siang yang cukup mewah dan sehat!
Begitulah sekelumit kisah gue ke Desa Wae Rebo. Kalau ditanya mau kesana lagi apa enggak? jawabannya MAUU BANGETT!
Those who find beauty in all of nature will find themselves at one with the secret of life itself – L.W. Gilbert